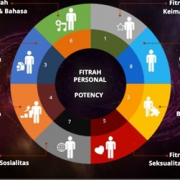Bahasa Kopi
اُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِى هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ
“Serulah (manusia) kepada jal an Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Q.S. Al-Nahl [16]: 125)
Salah satu kebiasaan yang ada di daerah penulis yang terryata sangat melekat dan sulit ditinggalkan adalah ‘ngopi’. Sepet rasanya sehari tanpa si hitam nikmat itu. Paling tidak, satu cangkir kopi satu hari sekali. Itu memang kebutuhan saya, bukan untuk jantan-jantanan, lanang-lanangan. Kalau jantan-jantanan berarti cuma macak jantan, artinya dia betina.
Dengan nyruput secangkir kopi panas, saya merasa menemukan dan menjadi diri saya sendiri. Bukannya berlebihan saya bilang seperti itu. yah, walau tiap orang emang beda, tidak sama. Ada orang yang ngopi karena hobi, buat nemenin nonton bola, begadang jaga ronda atau sebagai sarana menyambung silaturrahîm, cangkrukan sambil diskusi di pojokan kantor.
Kayak orang hidup. Kopi itu macam-macam, tapi tetap sensasinya yang khas itu ndak bakalan luntur. Dari warung yang di perempatan jalan hingga Coffe Shop mewah, dari kaki lima hingga hotel berbintang lima. Dari Arabica, Robusta, Kopi Aceh, Kopi Gayo, Kopi Lampung, Kopi Toraja, Kopi Bali, Kopi Wamena hingga si Kopi paling fenomenal Kopi Luwak. Dari yang eceran hingga kiloan. Dari bikinan si mbah di kampung hingga bikinan pabrik-pabrik yang gagah. Maka, saya yakin, bahwa Kopi itu adalah salah satu ‘minuman surga’. Lah wong nikmat banget je… Wallâhu‘alam
Saat nyruput kopi, baik sendiri terlebih pas jamaah, saat itu pula saya dapat nyruput pemahaman-pemahaman agama dan kehidupan lebih mendalam. Pemahaman hidup yang disajikan dengan aroma ketenangan tanpa ketergesa-gesaan. Damai dan tenteram. Bahkan tidak jarang saya dapat munguti pelajaran-pelajaran agama yang ternyata penuh kasih sayang, bukan yang ditampilkan di tipi-tipi itu. Ah, jauh bangetlah pokoknya. Karena saat ngopi keadaan kita cenderung menjadi netral, damai, tenang, tenteram dan slow. Sehingga pemahaman kita tentang ilmu agama pun ikut ngopi.
Kagak percaya? Ya udah coba saja intip ‘kemayoritasan’ kita dalam beragama. Khutbah-khutbah keagamaan, ceramah-ceramah dan makalah-makalah ilmiah dirasa kurang afdhal bila tidak disertai dengan dan disarati oleh nada geram dan murka. Seolah-olah tanpa gelegak kemarahan dan tusuk sana tusuk sini bukanlah khutbah dan makalah sejati. Kita akan sangat mudah menyaksikan dan mendengarkan khutbah “ustadz” yang dengan kebencian luar biasa menghujat pihak-pihak tertentu yang tidak sealiran atau sepaham dengannya. Nuansa nafsu atau keangkuhan “Orang Pintar Baru” (OPB) lebih kental terasa dari pada semangat dan ruh nasihat keagamaan dan ishlah.
Bahkan saya malu berkata saya Islam, kalo seandainya perilaku saya jauh dari ajaran Islam. Kanjeng Nabi Muhammad saja, yang pemahaman agama dan syari’atnya paling top-markotop, terbaik dari makhluk terbaik, dengan telaten mengajarkan Islam dengan bahasa kasih sayang, rahmatan lil’âlamîn, bukan dengan paksaan dan bahasa amarah. Lah kita ini, ngakunya ittiba’ Rasul, tapi justru lebih senang menggunakan bahasa-bahasa geram, bahasa-bahasa kekerasan, bahasa-bahasa kebencian. Kalau kita bisa berfikir tenang seperti saat ngopi, mungkinkah terjadi? Jangan cuma berani nongolin ayat tentang perang dong, yang baik-baik kan juga ada.
Maka seperti kata guru saya, Gus Mus, KH. Mustofa Bisri, bahwa atas nama Allâh banyak orang ‘menghina’ Allâh. Atas nama agama, justru banyak yang melecehkan Allâh. Atas nama kemanusiaan, banyak yang menindas manusia. Atas nama rakyat, banyak yang mengkhianati rakyat. Lalu, atas nama siapa dan apa sebenarnya hidup kita?
Di negeri kita yang bukan Arab, khususnya di zaman pasca orde baru ini, penyakit semacam ‘ashabiyah Jahiliyah itu rupanya juga mulai mewabah. Bukan kelompok suku dan agama saja yang difanatiki berlebihan, bahkan kelompok politik pun sudah cenderung difanatiki melebihi agama. Lebih celaka lagi – agaknya karena pemahaman soal politik dan demokrasi yang masih cingkrang di satu pihak, dan pemahaman atau penghayatan agama yang dangkal di lain pihak – fanatisme kelompok politik ini membawa-bawa agama. Maka campur-aduklah antara kepentingan agama, kepentingan politik dan nafsu.
Tidak jelas lagi apakah kepentingan politik mendukung agama atau agama mendukung kepentingan politik ataukah justru politik dan agama mendukung nafsu. Bahkan banyak mubalig atau da’i – yang seharusnya meneruskan misi kasih sayang Rasûlullâh shallallâhu ‘alaihi wa sallam. – entah sadar atau tidak, justru lebih mirip jurkam atau malah provokator yang tidak merasa risi mengeluarkan kata-kata kotor yang sangat dibenci oleh Nabi mereka sendiri.
Dakwah dan Amar Ma’ruf
Dakwah, seperti halnya banyak lafal yang berasal dari bahasa Arab, ketika masuk dalam perbendaharaan bahasa kita, mengalami pergeseran-pergeseran makna yang pada gilirannya juga berpengaruh kepada perilaku. Dakwah biasanya diartikan seruan dan propaganda. Dalam bahasa aslinya semula, dakwah mempunyai makna mengajak, memanggil, mengundang, meminta, memohon. Pendek kata makna-makna yang mengandung nuansa ‘halus’ dan ‘santun’. Sebagai istilah, dakwah yang kemudian dianggap sudah jelas maknanya ini, wallâhu a’lam bi al-shawwâb, tentunya bermula dari firman Allâh seperti dalam Q.S Al-Nahl [16]: 125. “Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mau’izhah hasanah (lafal-lafal yang ditulis miring, seperti diketahui, juga sudah menjadi istilah yang populer di kita) dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik…”(Gus Mus, 2010).
Perhatikanlah! dalam ayat itu perintah ‘Ud’u, ‘Ajaklah’ tidak disertai maf’ul bih atau objeknya seperti lazimnya fiil muta’addie. Para mufassir, biasanya ‘mengisi’ objeknya dengan al-nâs, manusia (Jadi, “Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu …dst”). Saya sendiri menganggap penambahan tafsir dengan objek berupa al-nâs, manusia, itu kok tidak perlu. Sebab kata-kata “ke jalan Tuhanmu” sudah cukup menjelaskan siapa yang disuruh Allâh ajak. Logikanya tentu –wallahu a’lam—yang diajak adalah mereka yang belum di “jalan Tuhan”. Karena mengajak orang yang belum di jalan Tuhan, maka –lagi-lagi wallahu a’lam—mesti dilakukan dengan hikmah dan mau’izhah hasanah.
Kalau pun harus berbantah, mesti dengan cara yang lebih bagus dari lawan berbantah. Dan perintah ini dilaksanakan dengan sangat sempurna oleh Rasûlullâh. Dengan lembut dan penuh kasih, dengan bijaksana dan nasihat yang baik, Rasûlullâh mengajak mereka yang belum berada di jalan Allâh. Bila perlu berbantahan, Rasûlullâh bersikap sangat santun. Hasilnya, dakwah beliau diterima dan orang-orang yang semula belum di jalan Allah pun berbondong-bondong menuju ke dan berjalan di jalanNya. Perintah ini juga dengan baik dilaksanakan oleh penerusnya, termasuk para wali, Wali Songo. (Bila penduduk negeri ini kemudian mayoritas berjalan di jalan-Nya, pastilah tidak terlepas dari dakwah mereka yang sesuai dengan arahan Qur’an itu). Bandingkanlah dengan dakwah masa kini yang nota bene hanya lebih kepada mereka yang sebenarnya sudah berada di jalan Allâh.
Amar makruf, berbeda dengan dakwah, bukan sekedar ajakan, tapi perintah, sebagaimana nahi adalah larangan, bukan sekedar himbauan. Amar makruf nahi munkar, adalah ciri komunitas kaum beriman (Baca misalnya, Q. 3: 110; 9: 71; dsb). Sebagai ciri, ia sama sebanding dengan rahmatan lil ‘âlamîn. Artinya –paling tidak menurut pemahaman saya—amar makruf nahi munkar itu tidak lain merupakan manivestasi atau pengejawentahan dari kasih sayang. Mengasihi dan menyayangi maka mengamar-makruf-nahi-munkari.
Muslim yang mukmin yang melakukan amar-makruf nahi-munkar, ibarat dokter yang mengobati pasiennya karena ingin mengobati. Dokter yang baik akan berusaha mengenali pasiennya dan mencari cara penyembuhan yang paling meringankan pasiennya. Jika harus memberi obat, sedapat mungkin mencarikan obat yang sesuai dengan pasiennya. Bila si pasien tidak mau disuntik atau tidak harus disuntik, sang dokter akan memberikan obat. Ini pun bila obat itu pahit, dipilihkan yang terbungkus kapsul, agar si pasien tidak merasakan pahitnya. Kalau pun terpaksa harus melakukan operasi, dokter tidak begitu saja membedah pasiennya, namun bermusyawarah dulu dengan keluarga si pasien. Karena dokter mengobati pasien, sebagaimana mukmin yang mengamar-makruf-nahi-munkari saudaranya, didasarkan kepada kasih sayang kemanusiaan. Bukan berdasarkan kebencian. (Gus Mus, 2010).
Mereka yang ber-amar-makruf-nahi(‘anil)munkar oleh dan dengan penuh kebencian, sebagaimana mereka yang berdakwah secara kasar dan provokatif, kiranya perlu meneliti diri mereka lagi. Apakah mereka melakukan itu atas dorongan ghirah keagamaan ataukah atas dorongan nafsu dan kepentingan lain. Atau mereka perlu lebih memperdalam pemahaman terhadap agama mereka, ajaran-ajaran, dan istilah-istilahnya. Jika tidak, disangkanya mendapatkan ridha Allah, alih-alih malah mendapatkan murkaNya. Nau’udzu billâh.
Lebih baik kita duduk sambil ngaduk kopi bareng. Sambil ngobrol-ngobrol soal “kita ini sebenarnya mau minggat kemana sih? nanti ‘dicari-cari’ Gusti Allah lho“. Dengan pikiran dan jiwa yang ikut ngopi, insya Allâh tidak bakal ada saling hujat, benci dan hajar. Seperti bahasa yang disajikan kopi, insya Allâh, pesan-pesan agama akan lebih terasa manis dan menentramkan. Wah, pasti sahdu.
Mohammad Taufiq Hidayat, Staff Prodi Hukum Islam FIAI UII
Artikel ini dipublikasikan dalam Buletin Jumat Al-Rasikh terbitan Direktorat Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam (DPPAI) Universitas Islam Indonesia (UII) edisi 28 September 2012. Artikel dapat diakses dari link ini.
Unduh Artikel